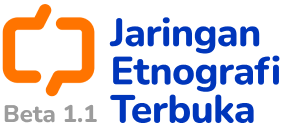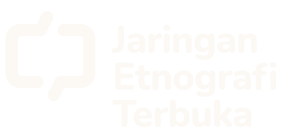Transkrip Episode 4 Podcast Jaringan Etnografi Terbuka

Transkrip Podcast JET Episode 3 Ada siapa di balik etnografi sukses? Cerita tentang I Madé Kalér – Wawancara dengan Amrina Rosyada, Bagian 2
Tito Ambyo
Halo dan selamat datang di podcast Jaringan Etnografi Terbuka. Sebuah ruang diskusi dan belajar tentang etnografi dan penjelajahan etnografi sebagai pendekatan yang terbuka dan kolaboratif. Saya Tito Ambyo dari RMIT University di Naarm, Melbourne, Australia dan bersama kita akan menyelami berbagai aspek etnografi. Ini adalah bagian kedua dari wawancara kita dengan Amrina Rosyada, mahasiswa S3 di Northwestern University. Kalau kamu belum mendengar episode sebelumnya, dengerin yang pertama dulu biar konteksnya lebih jelas. Di episode itu kita telah mendengar kisah tentang I Madé Kalér, intelektual lokal yang menjadi kunci dalam penelitian Margaret Mead yang menjadi legendaris di dunia antropologi secara umum. Namun, selama ini I Madé Kalér sering terlupakan dalam sejarah antropologi. Kita mendengar bagaimana Madé bukan sekadar asisten yang pasif melainkan kolaborator yang aktif yang menulis lebih dari 500 teks dan bahkan juga mengarahkan Mead untuk mengunjungi tempat-tempat penting di Bali. Namun kisah I Madé Kalér ini juga adalah sebuah contoh kompleksitas penelitian dalam etnografi atau bahkan juga di dunia jurnalisme di mana intelektual lokal dan narasumber sering harus menghadapi tantangan yang pelik yang tidak dihadapi oleh si jurnalis atau antropolog. Di episode ini kita akan mendengar dari Amrina tentang sisi lain dari kolaborasi antara Margaret Mead dengan I Madé Kalér termasuk bagaimana Madé secara sadar menyembunyikan informasi penting dari Margaret Mead. Seperti yang akan dijelaskan oleh Amrina, I Madé bilang bahwa tidak bisa sepenuhnya jujur tentang situasi kolonial di Bali pada waktu itu karena banyak hal terutama karena dia ingin menghindari ketidaksenangan dari pihak Belanda yang pada saat itu masih berkuasa di Bali. Kisah ini mengingatkan kita pada dilema yang dihadapi oleh anggota komunitas yang membantu memberikan informasi kepada peneliti atau kepada jurnalis. Mereka harus tahu caranya merambah realitas lokal untuk menemukan yang diperlukan oleh si antropolog atau oleh si jurnalis dan juga menghadapi bahaya yang ada di dunia lokal tersebut. Mari kita lanjutkan diskusi tentang apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman I Madé Kalér untuk praktik etnografi masa kini.
Tito Ambyo
Kita sekarang ngobrol tentang siapa di balik etnografi. Jadi sekarang kita tahu di balik etnografinya Margaret Mead, ada I Madé Kalér tapi di balik I Madé Kalér pun banyak orang-orang lain sebenarnya siapalah yang terlibat membantu I Madé Kalér dalam membantu Margaret Mead?
Amrina Rosyada
Benar, benar, benar. Yang pasti keluarganya, ibunya terutama. Ibunya Madé itu menjadi informan utama untuk topik tentang tari trance dance. Intinya tarian ini adalah ditarikan oleh penari yang dia tidak dalam keadaan sadar. Jadi ibunya itu banyak menjadi informan dalam hal itu karena Margaret Mead sangat terobsesi ya sama trance ini atau ketidaksadaran ketika melakukan tari dalam riset dia tentang schizophrenia di Bali. Terus, habis itu ada juga sepupunya yang dia sebenarnya gak terlalu banyak menjadi informan tapi dia, karena dia adalah seniman wayang, itu dia banyak membuat wayang yang dibawa pulang ke New York sama Margaret Mead dan akhirnya disimpan di sana sebagai koleksi Bali mereka yang sangat bisa dikunjungi kalau mau riset tentang kesenian Bali di Amerika. Itu sih mungkin dua orang yang prominent yang aku bisa lihat di arsip itu ibunya dan sepupunya.
Tito Ambyo
Kan I Madé Kalér itu tadi Amrina bilang menentukan arah penelitiannya Margaret Mead? Tapi, juga yang kita tahu I Madé Kalér menyembunyikan beberapa hal dari Margaret Mead.
Amrina Rosyada
Iya, betul. Jadi, pada waktu Margaret Mead melakukan penelitian di Bali, itu Madé menurut wawancara dia dengan seorang peneliti namanya Tessel Paulman tahun 70-an atau 80-an gitu wawancara ini dilakukan itu Madé bilang kalau dia tidak sepenuhnya jujur tentang situasi kolonial di Bali pada waktu itu. Dan sebagai disclaimer ini informasi ini bukan aku yang menemukan tapi aku menemukannya dari sumber sekunder, ya, dari tulisannya si Tessel Paulman tahun 1990 jadi aku tidak menemukan info ini di arsip tapi info ini ditemukan melalui wawancara langsung dengan orangnya pada waktu itu, 50 tahun setelah risetnya dilakukan. Itu Madé bilang bahwa tidak bisa sepenuhnya jujur tentang situasi kolonial di Bali pada waktu itu karena banyak hal, terutama tentang dia ingin menghindari ketidaksenangan pihak Belanda tentang informasi tersebut kalau dia memberikan informasi itu kepada Margaret Mead gitu. Jadi seperti banyak peneliti barat yang meneliti Bali pada waktu itu pada tahun 1930-an ke bawah, itu banyak, si Margaret Mead itu melihat Bali sebagai kayak surga ya karena udah asri, banyak pohon hijau, orang-orangnya ayem, pada santai gitu, terus habis itu makanan melimpah, di ritual-ritual selalu ada makanan. Padahal, pada kenyataannya, Bali pada waktu itu adalah salah satu daerah yang mana pajaknya paling tinggi di Hindia Belanda terus waktu itu juga banyak wabah seperti TBC yang membunuh banyak anak-anak juga banyak petani miskin itu mereka termiskinkan lah istilahnya petani-petani Bali pada waktu itu cuman Madé pada waktu itu memutuskan untuk tidak membagikan informasi tersebut ke Margaret Mead karena, ya itu tadi, masalah keselamatan Margaret Mead dan diri dia sendiri dan juga dia memutuskan untuk nggak nge-share karena menurut pengamatannya, ini juga menurut wawancara di tulisannya Tessel Paulman, itu Madé melihat kalau Margaret Mead sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama masalah politik di Bali pada waktu itu. Jadi dia pada waktu itu yang namanya antropologi atau etnografi itu sangat terpisah dari masalah perpolitikan gitu ya. Jadi Margaret Mead itu sangat nggak mau tau lah tentang masalah perang pasifik atau kolonialisme di Bali pada waktu itu. Jadi akhirnya Madé mikir yaudah lah it’s not worth it dan yaudah akhirnya dia nggak jujur sepenuhnya tentang itu dan menurutku itu juga jadi salah satu bukti kalau tugasnya I Madé Kaler pada waktu itu tuh nggak cuma cari data tapi juga menavigasikan hal-hal seperti ini kan hal-hal yang berhubungan dengan politik dan keselamatan dirinya dan juga kolaborator dia, si Margaret Mead ini, jadi itu juga salah satu bentuk labor menurutku: menavigasikan hal-hal seperti ini dan itu harus kita pikirkan lebih jauh ya harus lebih diperhatikan bagaimana hal ini tuh bisa menjadi salah satu bentuk labor juga gitu.
Tito Ambyo
Ya, mungkin ini menarik untuk yang mau melakukan penelitian antropologi, mau melakukan penelitian etnografi, kemudian pergi ke sebuah komunitas kemudian menemukan wah ini ada yang asik banget nih untuk dijadiin informan gitu kan, tapi kemudian kadang-kadang kita lupa juga gitu bahwa si informan ini juga…mungkin kalau menariknya kalau dibandingin sama jurnalisme gitu ya, jurnalisme itu kan banyak apa namanya koresponden-koresponden luar negeri, koresponden-koresponden gitu yang ke Indonesia ke negara-negara di timur tengah, kemudian mereka jadi pahlawan gitu kan muncul di TV tapi kita gak ngeliat gitu bahwa di balik mereka tuh ada fixer gitu kan, orang-orang yang bantuin. Bahkan kayak kalau misalnya di zona-zona perang gitu kan yang tahu harus kemana biar aman tuh ya fixer-nya gitu, tapi fixer tuh sering gak ada yang tahu gitu.
c
Aku baru tahu bahkan tentang fixer ini.
Tito Ambyo
Ya, menarik sih. Dan sekarang ini juga jadi pembicaraan sih di jurnalisme apakah sebaiknya fixer itu dinamakan sebagai jurnalis juga gitu kan, yang menurut gue sih ya iyalah. Tapi, juga ada yang menariknya, kenapa gue mikirin itu karena banyak fixer yang juga gak mau jadi terkenal kan karena kerjaan mereka berbahaya kan jadi kalau misalnya sampai nama mereka diketahui sama pemerintah lokal kan jurnalisnya bisa pulang ke Australia, ke Amerika sedangkan orang-orang kayak I Madé Kaler, dia harus tinggal di Bali lagi gitu kan. Jadi, kalau dia, kalau kita sebagai peneliti etnografi terus ke sebuah komunitas terus nanya-nanya hal-hal yang kontroversial gitu kan kita harus ingat juga nih, apa, wah iya gue bisa balik ke universitas aman tapi informan kita kalau misalnya hidupnya sampai, kalau kita maksa mereka bicara tentang hal-hal yang kontroversial itu bisa bahaya juga buat mereka gitu, kan?
Amrina Rosyada
Iya, betul, persis, persis.
Tito Ambyo
Nah, esai Anda ini yang tentang Who Made Mead yang berbicara tentang I Madé Kaler yang diterbitkan di majalah Sapiens itu dikutip kan sama Gunel dan Watanabe yang mereka menulis tentang patchwork etnography. Dan patchwork etnography itu menarik untuk ya mungkin ya teman-teman juga nih yang lagi mau memulai penelitian etnografi, kan ini juga masalah yang gue pernah mikir sih, karena gue kerja di Australia, sekalian PhD, dan karena pengen antropologi jadi harus etnografi gitu kan. Tapi terus gue mikir terus apakah gue harus meninggalkan kehidupan gue selama satu tahun gak ada gaji gak ada apa untuk tinggal bersama sebuah suku bangsa apa di desa mana dan gue jadi mikir apakah gue harus seperti itu gitu ya? Karena kan kalau lihat sejarahnya antropologi kayak tadi Margaret Mead gitu kan yang harus ya kemudian tinggal dengan komunitas kemudian dimasakin segala macem. Sedangkan sekarang kita hidup di dunia universitas neoliberal, yang misalnya gue ke RMIT bilang eh gue mau cabut ke Indonesia nih mau penelitian satu tahun, oke gaji gue terus ya, gitu kan, gak akan dapet lah. Kemudian sekarang ada patchwork etnography yang bilang oh mungkin kita harus lebih terbuka lah dengan keterbatasan-keterbatasan dan mungkin kita cuma bisa penelitian sedikit-sedikit kemudian pulang kemudian penelitian lagi, tapi juga kita harus lebih terbuka dengan fakta bahwa antropologi itu selalu selalu kolaboratif gitu ya? Dan Anda sendiri juga menulis di artikel itu bahwa antropologi selalu interkultural dan kolaboratif. Dan apakah ini berarti kita harus berhenti nih memuliakan orang-orang seperti Geertz, Boas, Mead? Seperti apa nih harusnya kita membaca karya-karya mereka sekarang?
Amrina Rosyada
Menurutku berhenti memuliakan tentu perlu, tapi berhenti membaca not necessarily. Kupikir gak harus begitu ya. Berhenti memuliakan tuh gak sama dengan berhenti engaging atau berhenti membaca karya-karya mereka gitu. Karena menurutku dengan membaca karya-karyanya Geertz, Boas, dan Mead atau siapapun lah orang-orang antropolog zaman dahulu yang mungkin punya studi yang agak-agak problematis gitu itu, kita dengan membaca karya mereka kita bisa mengkritik juga gitu loh. Membaca kan bukan hanya sesuatu yang kita lakukan secara pasif ya, membaca tuh bukan yang terus kita baca langsung terus kita menginternalisasi. That’s not how I see reading gitu. Jadi ketika aku bilang kita harus tetap membaca karya-karya mereka itu kita membaca mereka dengan lensa yang lebih kritis dan hanya karena kita membaca mereka kita bisa mengkritisi ide-ide mereka yang mungkin udah gak sesuai sama antropologi zaman sekarang kayak gitu. Jadi kupikir kita perlu berhenti memuliakan mereka, tapi I think kita masih perlu membaca karya-karya mereka gitu. Dan kalau kita bicara alternatifnya apa kalau misalnya kita berhenti memuliakan orang-orang seperti itu mungkin ada dua cara ya yang aku bisa pikirkan sekarang. Pertama, kita bisa mendiversifikasi pentolan-pentolan atau superstar-superstar yang kita pelajari di teori antropologi gitu, misal dengan memasukkan antropolog-antropolog dari negara lain atau dari kultur lain seperti itu kan. Misal di Amerika sendiri ada Zora Neale Hurston yang dia juga satu angkatan sama Mead tapi dia adalah seorang antropolog kulit hitam, misalnya. Atau dengan ya itu tadi kayak misal memasukkan Koentjaraningrat dalam, apa, dalam kurikulum, itu udah I think that’s a good step toward decolonizing the canon gitu. Terus, yang kedua bisa juga dengan cara untuk kita melihat, kita gak cuma menitikberatkan individualisme dalam scholarship atau dalam akademia, tapi kita menitik beratkan kolaborasi. Jadi selama ini kan kita mungkin ngelihat teori antropologi selalu orang ini, orang ini, orang ini individual gitu kan kayak oh Mead, dia Margaret Mead dia kontribusinya ini, ini, itu dalam antropologi, tapi mungkin kita harus agak menjauh dari itu dan kita melihat bagaimana sih karya Mead ini itu adalah sebuah karya yang dibentuk melalui proses kolaboratif gitu instead of dia sendiri mikir tentang teori atau dia memproduksi teori gitu jadi mungkin dua hal itu yang bisa aku tawarkan sekarang.
Tito Ambyo
Ya, dan Zora Neale Hurston itu menarik ya karena, udah denger ini Zora’s Daughters podcast?
Amrina Rosyada
Belum.
Tito Ambyo
Ini gue bisa rekomen buat teman-teman juga nih. Terakhir nih untuk menutup pembicaraan ini. Jadi kita udah bicara banyak tentang siapa aja yang terlibat dalam etnografi bukan cuma informan tapi juga teman-temannya dan keluarga informan, jadi banyak banget yang terlibat dalam etnografi dan kita harus berhenti juga memuliakan apa ya orang-orang, individu-individu terutama terutama mungkin individu-individu yang datang ke negara-negara yang mereka gak bisa bahasanya, segala macem. Sekarang gimana nih? Kan ini nama podcast ini etnografi terbuka nih, jadi kita mau berdiskusi tentang gimana sih cara etnografi yang lebih terbuka? Dari penelitian Amrina sampai saat ini apa nih kesimpulannya? Seperti apa kalau kita mau penelitian antropologi, seperti apa kita mempraktikan etnografi yang lebih terbuka, lebih nyaman dengan kolaborasi?
Amrina Rosyada
Ini aku berangkat dari risetku ya, karena pasti ada banyak sekali cara untuk membuat etnografi lebih terbuka tentang kolaborasi. Tapi, berkaca dari risetku, itu adalah, risetku ini kan intinya mengkritik bagaimana para antropolog atau para scholars, para akademisi itu berhenti pada, berhenti untuk memberikan, apa ya, kredit kepada asisten-asisten mereka itu cuman dari caranya, apa ya, menuliskan nama mereka di footnotes gitu misalnya atau di akhir terima kasih kepada siapa-siapa gitu ya, jadi kayak cuman disebutkan angin lalu aja gitu. Jadi kalau aku berkaca dari risetku aku ingin mendorong adanya refleksi yang lebih menyeluruh terutama di bagian metode, bagaimana kita bisa mendiskusikan atau apa ya including orang-orang seperti Madé ini dalam section metode kita gitu. Misalnya, kita ngomongin gimana sih orang-orang seperti Madé dan orang-orang, kolaborator-kolaborator lainnya itu membentuk pengetahuan kita tentang lapangan atau tentang sebuah isu instead of hanya menyebutkan oh orang ini membantu saya mengumpulkan data gitu. Tapi mungkin kita bisa menggali hal itu satu langkah lebih dalam satu langkah lebih jauh, gimana sih mereka itu bisa ya itu tadi kayak membantu kita atau membentuk pemikiran kita tentang sebuah isu atau apa yang kita sebut dengan lapangan kayak gitu.
Tito Ambyo
Ya, masuk akal dan mungkin jadi seperti ini ya apa kan kalau misalnya baca skripsi-skripsi itu biasanya yang paling pertama kita baca itu ya terima kasih untuk ini, ini, ini banyak banget gitu kan yang ditulis. Mungkin jangan cuma dijadikan dalam halaman terima kasih tapi masukin ke metode gitu ya? Bahwa ini membantu saya dengan ini dan ini yang saya pelajari tentang ini gitu ya?
Amrina Rosyada
Betul karena di bagian metode inilah kita punya ruang untuk lebih jujur dan lebih terbuka kan kupikir, karena kadang-kadang kita ngomongin tentang kesulitan atau kayak tantangan itu kan di bagian metode. Tapi, kenapa kita, what stops us from talking about bagaimana kolaborator membantu kita gitu? Dan dibutuhkan ini ya, apa, dibutuhkan humbleness juga untuk mengaku itu kan. Kita juga butuh apa ya untuk bisa jujur bahwa kita gak tau semuanya atau bahwa kita dapat pengetahuan tertentu dari orang lain sebagai peneliti. Itu kan dibutuhkan kebesaran hati untuk mengaku itu. Dan kupikir itu yang dibutuhkan bagi para peneliti gitu, bahwa gak apa-apa loh gak tau semuanya dan gak apa-apa loh kalau kita ngaku kalau kita dapet pengetahuan ini atau kita dapet pola pikir tertentu dari bukan dari diri kita doang, tapi juga dari kolaborasi dengan orang lain.
Tito Ambyo
Ada apa lagi yang mau ditambahin gak tentang I Madé Kalér atau tentang asisten-asisten antropologi ini?
Amrina Rosyada
Mungkin untuk kasus, apa ya, untuk konteks hari ini gitu kupikir riset ini mudah-mudahan bisa menjadi pijakan untuk kita bisa berefleksi bagaimana kita bisa memperlakukan kolaborator kita dengan lebih adil dan lebih manusiawi gitu. Karena sebetulnya ketika aku menuliskan ini aku juga gak bisa melupakan masa-masa dimana aku juga bekerja sebagai asisten riset untuk peneliti-peneliti asing gitu dan, apa ya, ini kupikir bisa menjadi curahan hati dari pengalamanku sendiri yang mudah-mudahan bisa menjadi, ya itu tadi, refleksi agar kita bisa memperlakukan kolaborator kita secara lebih adil gitu.
Tito Ambyo
Dan kalau kita nyelesain ceritanya I Madé Kalér terus apa yang setelah dia berhenti jadi asisten Mead apa yang terjadi sama dia nih?
Amrina Rosyada
Dia itu sebetulnya diundang oleh Margaret Mead untuk menjadi asisten dia di New York gitu karena Margaret Mead mikir si I Madé Kalér ini bisa menjadi sukses disana sebagai native interlocutor gitu ya, ditanya-tanyain gitu kan, atau even si Margaret Mead itu juga ngundang Madé ini untuk ikut ke Belanda gitu. Tapi si Madé menolak. Secara sadar dia bilang ah aku gak pengen jauh dari keluargaku, aku cuman pengen kalau misalnya pun aku harus pergi aku cuman bisa sejauh Jawa aja aku perginya, aku gak mau jauh-jauh gitu. Akhirnya dia tetap di Indonesia dia beberapa kali pindah kerjaan. Dia kerja di misalnya di dia sempat kerja setelah kerja sama Margaret Mead itu dia di KPM, apa namanya, semacam maskapai kapalnya Belanda gitu, sebagai tour guide tapi dia gak suka kerja disitu karena dia harus bertemu dengan turis-turis yang perilakunya menjijikan alias mereka suka ya mengeksotifikasi perempuan Bali atau tentang Bali. Jadi dia kurang suka dengan itu. Akhirnya dia jadi guru. Dia menjadi guru SD yang mana dia sangat sangat passionate di situ, dia senang menjadi guru SD. Dan dari kartu pos-kartu pos yang aku baca di arsip itu juga, dia memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi dan memiliki semangat antikolonialisme yang sangat tinggi juga. Dia sempat tanya ke Margaret Mead ketika dia sudah jadi guru, mungkin sekitar 20 tahun 30 tahun setelah riset itu, dia ngirim surat ke Margaret Mead, dia minta bisa gak ngirim buku bahasa Inggris untuk sekolahku di Bali, karena ada banyak nih anak-anak di Bali yang gak bisa bahasa Inggris, gak bisa baca kayak gitu. Jadi dia memutuskan secara sadar untuk tidak menapaki jalan menjadi akademisi atau menjadi native interlocutor gitu walaupun masih banyak kadang-kadang peneliti-peneliti asing dari Amerika yang mereka dapat rekomendasi dari Margaret Mead untuk bertemu I Madé Kalér gitu. Tapi ya dia akhirnya jadi guru sampai dia meninggal gitu.
Tito Ambyo
Terima kasih telah mendengarkan bagian kedua dari percakapan kami dengan Amrina Rosyada tentang I Madé Kalér. Dari diskusi ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita bawa ke dalam praktik etnografi masa kini.
Pertama, kolaborasi dalam etnografi melibatkan jaringan yang jauh lebih luas dari yang sering kita bayangkan. Di balik I Madé Kalér ada ibunya yang menjadi informan utama tentang tari trans, sepupunya yang membuat wayang untuk koleksi museum, dan banyak orang lain yang kontribusinya sering tidak terlihat.
Kedua, keputusan I Madé Kalér untuk menyembunyikan realitas kolonial dari Margaret Mead mengingatkan kita bahwa kolaborator memiliki agensi dan pertimbangan sendiri. Mereka bukan sekadar sumber, tetapi manusia yang harus mempertimbangkan keselamatan dan konsekuensi jangka panjang dari proses penelitian.
Ketiga, seperti “fixer” dalam jurnalisme, asisten penelitian lokal sering menghadapi risiko yang tidak dialami peneliti utama. Kita sebagai peneliti bisa pulang ke universitas dengan aman, sementara mereka tetap harus hidup dalam konteks yang kita teliti.
Keempat, dekolonisasi dalam dunia pengetahuan bukan berarti membuang semua karya klasik, melainkan membacanya secara kritis dan juga mendiversifikasi apa yang kita baca dan anggap sebagai bagian dari kanon. Dan juga sebagai pembaca dan peneliti, salah satu yang penting adalah menekankan sifat kolaboratif dari produksi pengetahuan.
Dan yang terakhir, etnografi terbuka memerlukan perubahan praktis: mengakui kontribusi kolaborator bukan hanya dalam ucapan terima kasih, tetapi dalam bagian metodologi kita. Kita perlu menjelaskan dengan jujur bagaimana kolaborator membentuk pemahaman kita tentang lapangan.
Terima kasih kepada Amrina Rosyada yang telah berbagi penelitian dan pemikirian yang sangat berharga ini. Jangan lupa berlangganan dan bagikan episode ini kepada teman-teman yang tertarik dengan etnografi dan dekolonisasi dalam dunia penelitian. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga JET, terutama Annisa Beta, Ben Hegarty, Fikri Haidar, Eni Puji Utami, Amrina Rosyada sebagai narasumber, untuk Rosie Clynes untuk komposisi musik, Rugun Sirait untuk editing, dan juga Anda sebagai pendengar. Saya Tito Ambyo untuk Podcast Jaringan Etnografi Terbuka. Sampai jumpa di episode selanjutnya.